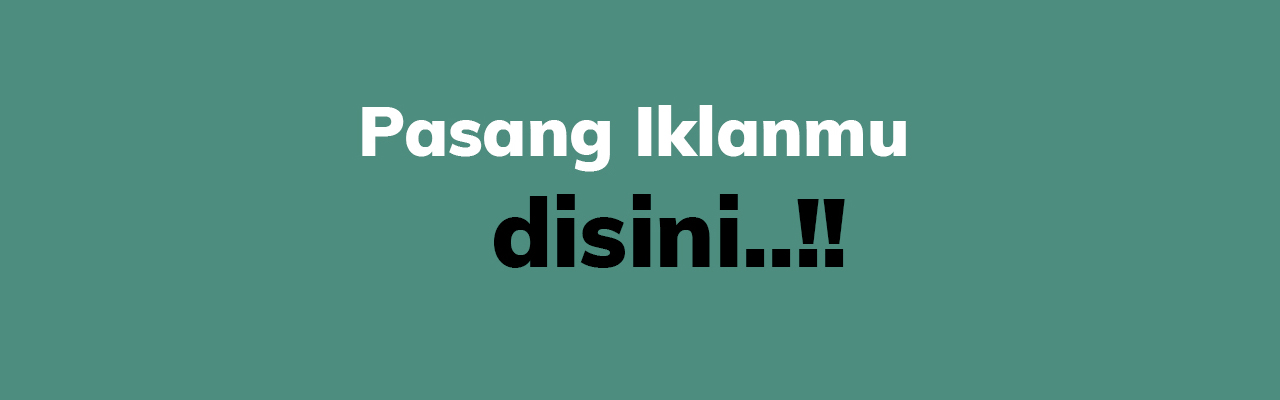Tekno & Sains
Test Post Teknologi & Sains
Published
7 years agoon
By
AdminYou may like

PKBM disebut semakin strategis sebagai jalur pendidikan kesetaraan, setelah Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengungkap banyak anggota DPR yang ternyata lulusan Paket C dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI.
Abdul Mu’ti menegaskan bahwa program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) menjadi salah satu kunci pemerintah untuk menurunkan angka putus sekolah di Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa jalur kesetaraan, khususnya Paket C yang setara SMA, telah melahirkan banyak figur publik, termasuk anggota legislatif di Senayan. Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pernyataannya memicu tawa para anggota dewan yang hadir.
“Banyak anggota dewan yang juga lulusan Paket C,” kata Abdul Mu’ti dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Januari 2026.
Ia menambahkan bahwa peserta pendidikan kesetaraan di berbagai PKBM didominasi oleh peserta Paket C, menunjukkan bahwa jalur ini menjadi pilihan realistis bagi mereka yang tidak bisa mengakses sekolah formal. Pernyataan itu sekaligus ingin menghapus stigma negatif terhadap pendidikan kesetaraan dan menunjukkan bahwa lulusan Paket C dapat berkompetisi hingga ke lembaga legislatif nasional.
Paket C adalah program pendidikan kesetaraan setara SMA bagi warga yang tidak menyelesaikan pendidikan formal, yang diselenggarakan melalui PKBM dan satuan pendidikan nonformal lain. Menurut Abdul Mu’ti, penguatan PKBM merupakan strategi penting untuk memperluas akses pendidikan, terutama bagi kelompok masyarakat yang selama ini tersisih dari jalur sekolah reguler. Ia menyampaikan penjelasan ini saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, yang menyoroti perlunya perluasan akses pendidikan bagi kelompok yang sulit dijangkau sistem formal.
Abdul Mu’ti juga bercerita tentang kunjungannya ke salah satu PKBM di Majalengka, Jawa Barat, yang mampu menampung lebih dari 300 peserta didik. Mayoritas peserta di PKBM tersebut mengambil program Paket C, yang menurutnya menggambarkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap layanan pendidikan setara SMA di luar sekolah formal.
“Saya baru pulang dari Majalengka, ada PKBM yang dikelola oleh temannya Pak Lalu. Ternyata sampai ratusan, 300-an lebih. Dan yang paling banyak itu Paket C,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya penataan kelulusan di pendidikan kesetaraan agar sesuai jenjang dan tidak terjadi praktik kelulusan yang melompati tahap.
“Paket C lulus dulu, Paket B menyusul. Itu tidak boleh terjadi lagi,” ujar Mu’ti yang menekankan pentingnya kelulusan sesuai jenjang.
Abdul Mu’ti menyoroti bahwa angka anak tidak sekolah di Indonesia masih tergolong tinggi. Menurutnya, faktor penyebab putus sekolah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga faktor kultural dan geografis. Ia mencontohkan pernikahan usia dini dan keterbatasan akses pendidikan di wilayah tertentu sebagai hambatan yang sering dihadapi masyarakat.
“Angka tidak sekolah kita cukup tinggi, dan sebagiannya itu bukan semata-mata karena ekonomi, tapi sebagian karena alasan kultural, misalnya menikah di usia muda, atau karena geografi,” ungkap Abdul Mu’ti.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka putus sekolah masih terjadi di berbagai jenjang, terutama di tingkat SMP dan SMA/sederajat, meskipun tren jangka panjangnya cenderung menurun beberapa tahun terakhir. Media nasional lain juga mencatat bahwa pendidikan kesetaraan, termasuk Paket A, B, dan C, menjadi salah satu instrumen untuk mengejar target peningkatan rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia.
Untuk menjawab berbagai persoalan akses pendidikan tersebut, pemerintah berencana memperluas dan memperkuat PKBM, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di luar negeri. Abdul Mu’ti menyebut bahwa masalah pendidikan anak Indonesia di luar negeri tidak hanya dialami anak pekerja migran, tetapi juga anak-anak diplomat dan warga negara Indonesia lain yang tinggal di luar negeri.
Ia menegaskan bahwa peserta didik pendidikan kesetaraan melalui PKBM berhak mendapatkan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) sebagaimana peserta didik di satuan pendidikan lain. Penguatan tata kelola, pendanaan, dan pengawasan PKBM disebut penting agar kualitas pendidikan kesetaraan terjaga dan lulusannya diakui setara dengan pendidikan formal.
Mu’ti juga menilai bahwa keberhasilan alumni Paket C yang kini duduk sebagai anggota legislatif bisa menjadi contoh bahwa jalur pendidikan kesetaraan bukan “jalan belakang”, melainkan bagian sah dari sistem pendidikan nasional. Media seperti Tempo dan berbagai portal berita nasional lainnya menyoroti pernyataannya sebagai penegasan bahwa lulusan PKBM dan Paket C dapat berkontribusi di ruang publik dan politik nasional.
News
Bukan Cari Untung: Elon Musk Gratiskan Starlink untuk Wilayah Terdampak Banjir Sumatra
Published
3 months agoon
01/12/2025
NEWS – Layanan internet satelit Starlink milik Elon Musk menyediakan akses internet tanpa biaya bagi warga yang terdampak banjir dan longsor di berbagai wilayah Sumatra, termasuk Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat. Kebijakan ini berlaku bagi pelanggan baru maupun pelanggan lama yang berada di zona terdampak hingga akhir Desember 2025, dengan tujuan menjaga komunikasi di tengah terputusnya jaringan telekomunikasi darat.
Banjir dan tanah longsor di Sumatra dalam beberapa hari terakhir telah merusak infrastruktur, memutus akses jalan, dan melumpuhkan ratusan situs transmisi telekomunikasi, sehingga banyak kawasan sempat terisolasi tanpa koneksi internet. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat ratusan dari puluhan ribu site telekomunikasi di Sumatra Utara tidak berfungsi akibat bencana, sehingga konektivitas satelit menjadi salah satu solusi utama untuk mendukung koordinasi evakuasi, penyaluran bantuan, serta komunikasi keluarga.
Melalui unggahan di akun X pribadinya, Elon Musk menjelaskan bahwa pemberian akses gratis Starlink dalam situasi darurat sudah menjadi prosedur baku di perusahaan. Dalam pernyataannya, Musk menulis: “Kebijakan standar SpaceX adalah menggratiskan Starlink setiap kali terjadi bencana alam di suatu tempat di dunia. Tidak lah benar mengambil untung dari musibah,” ujar Elon Musk melalui akun X @ElonMusk dikutip Sabtu (29/11/2025).
Starlink juga menyampaikan keterangan resmi bahwa layanan ini ditujukan khusus bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia. Dalam pengumumannya di X, perusahaan menyatakan: “Bagi mereka yang terdampak banjir parah di Indonesia, Starlink menyediakan layanan gratis bagi pelanggan baru dan lama hingga akhir Desember. Kami juga bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk segera membangun terminal dan memulihkan konektivitas ke wilayah-wilayah terdampak paling parah di Sumatra,” tulis Starlink dalam pernyataan resminya di X pada Sabtu (29/11/2025).
Koordinasi dengan pemerintah Indonesia mencakup percepatan distribusi dan relokasi terminal Starlink ke lokasi-lokasi yang paling terdampak, terutama daerah yang akses jalannya terputus dan jaringan seluler konvensional lumpuh. Sejumlah laporan menyebut bahwa perangkat Starlink juga dimanfaatkan aparat kepolisian dan tim darurat di Sumatra Utara untuk membuka kembali jalur komunikasi bagi warga yang terisolasi, sehingga mereka dapat menghubungi keluarga dan menyampaikan kebutuhan mendesak.
Secara teknis, jaringan Starlink memanfaatkan ribuan satelit orbit rendah yang mengirimkan koneksi langsung ke antena pengguna, sehingga layanannya relatif tetap aktif meski jaringan kabel optik dan menara telekomunikasi di darat mengalami kerusakan. Di Indonesia, Starlink telah memperoleh izin beroperasi sejak Mei 2025 dan sebelumnya diproyeksikan terutama untuk melayani wilayah pedalaman, namun kini perannya meluas sebagai infrastruktur komunikasi darurat saat bencana besar.
Langkah Starlink di Sumatra sejalan dengan pola respons perusahaan di negara lain yang pernah dilanda bencana, seperti Jamaika dan Bahama setelah Badai Melissa, maupun di Cape Verde pasca-badai pada Agustus 2025, di mana layanan darurat serupa juga digelar untuk menjaga konektivitas warga. Berbagai media internasional dan nasional menilai kebijakan penggratisan ini sebagai bagian dari strategi global Starlink untuk memposisikan jaringan satelit mereka sebagai tulang punggung komunikasi di daerah bencana.
Beberapa media nasional arus utama mengonfirmasi bahwa akses gratis Starlink di zona banjir Sumatra berlaku selama sekitar satu bulan, hingga akhir Desember 2025, bagi pelanggan yang sudah ada maupun yang baru mendaftar di wilayah terdampak. Laporan lain menyebut, warga di area bencana dapat mengajukan layanan melalui mekanisme dukungan khusus yang disiapkan Starlink, sedangkan perangkat terminal dikoordinasikan bersama instansi pemerintah dan tim tanggap darurat di lapangan.
News
Fotografer Wajib Izin: Perlindungan Data Pribadi Jadi Sorotan Regulasi Fotografi
Published
4 months agoon
29/10/2025
NEWS – Masyarakat Indonesia kini dihadapkan pada fenomena pemotretan warga di ruang publik yang kian marak tanpa izin. Seorang fotografer bisa menghadapi gugatan jika fotonya disebarluaskan tanpa persetujuan pemilik gambar, menurut sumber berita terkini dan berbagai analisis hukum terkait. Regulator dan pihak berwenang menegaskan bahwa perlindungan data pribadi serta hak atas privasi tetap menjadi prioritas di era digital, meskipun foto tersebut diambil di tempat umum.
Dalam konteks ini, Komisi Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pentingnya etika dan kepatuhan hukum dalam fotografi publik. Selama beberapa hari terakhir, pandangan ahli hukum dan publikasi media besar menyoroti bahwa penyebaran foto warga tanpa izin bisa melanggar hak asasi manusia serta UU PDP, tergantung pada konteks penggunaan fotonya.
Sejumlah pakar hukum menekankan bahwa foto seorang individu tetap termasuk data pribadi, sehingga penyebaran atau komersialisasian tanpa persetujuan bisa menimbulkan konsekuensi hukum. Salah satu pandangan yang banyak dirujuk adalah bahwa tindakan tersebut bisa dikenai berbagai pasal terkait hak cipta, perlindungan data pribadi, hingga undang-undang ITE jika ada unsur penjualan atau penyebaran untuk kepentingan komersial. Analisis ini sejalan dengan interpretasi para pakar di berbagai media arus utama yang juga menyoroti pemisahan antara penggunaan foto untuk pemberitaan dan penggunaan komersial.
Salah satu narasumber kunci menegaskan bahwa perlindungan identitas dan wajah individu tetap menjadi hak pribadi, meskipun berada di ruang publik. Narasumber lain menekankan bahwa konteks penggunaan foto—terutama jika untuk kepentingan komersial—memiliki bobot hukum yang berbeda dibandingkan penggunaan untuk pemberitaan atau dokumentasi umum.
Di sisi regulator, arah kebijakan menunjukkan fokus pada peningkatan literasi digital dan etika penggunaan teknologi fotografi, termasuk dalam konteks AI. Upaya kolaborasi antara fotografer, asosiasi profesi, serta platform digital digalakkan untuk memperkuat pemahaman mengenai hak cipta, privasi, dan tanggung jawab sosial di era digital.
Para profesional media juga menekankan pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan foto warga tanpa persetujuan, karena dampaknya bisa meluas, mulai dari kerugian reputasi hingga potensi tindakan hukum. Seiring dengan itu, sejumlah kanal berita nasional dan internasional memperkuat pemahaman publik melalui liputan analitis mengenai bagaimana hukum Indonesia mengatur perlindungan data pribadi dan hak atas gambar.
Keseimbangan antara kebebasan berekspresi, kepentingan publik, serta hak individu menjadi inti diskusi. Para ahli hukum menilai perlunya regulasi yang lebih jelas untuk menghadapi dinamika teknologi pemotretan dan AI generatif, tanpa mengabaikan hak privasi warga.

Ramadan Semakin Hidup! Wali Kota Adhan Gaungkan Tadarus Al-Qur’an di Seluruh Kota Gorontalo

Resmi Diumumkan! Pemkab Pohuwato Putuskan Zakat Fitrah Rp40 Ribu

Awal Ramadan Duka: Kecelakaan di Pohuwato Tewaskan Warga Balayo

Kecelakaan Maut di Pohuwato, Diduga Libatkan Truk dan Sepeda Motor

Suara Tradisi di Tengah Zaman: Koko’o Bilungala Tetap Berdentum Tanpa Sound System

Klarifikasi Penting! UNG Tegaskan Penelitian Mikroplastik Tak Ganggu Nelayan Torosiaje

Tertib Administrasi! Pemkab Pohuwato Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan

Bahlil: Saya Menteri Gagal Kalau Saudara Kita di Desa Belum Menikmati Listrik

Tak Sekadar Rayakan HUT, Gerindra Gorontalo Ulurkan Kasih untuk Anak Yatim dan Piatu

Protes Menggema: Peserta Mubes IX LAMAHU Nilai Pemilihan Ketua Umum Tak Demokratis

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-

 Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months agoMenolak Lupa: Tragedi 2 Januari 2025, Ketika Keadilan untuk Julia Belum Datang
-

 Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months agoBukan Rapat Biasa, Instruksi Gerindra Tegaskan Kader Harus Kompak dan Berdampak untuk Mayoritas Rakyat
-

 Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months agoJIKA 100 TAHUN LAGI ORANG MENCARI GORONTALO 2025
-

 Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months agoBerawal dari Arahan Wali Kota, Kelurahan Biawao Raih Juara Pemungutan PBB-P2
-

 Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months agoAbai dan Bungkam: Refleksi Elit Gorut Atas Tragedi Julia
-

 Advertorial2 months ago
Advertorial2 months agoBukan Sekadar Imbauan! Wali Kota Gorontalo Tegas Larang Petasan di Malam Tahun Baru
-

 Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months agoPotret Ironi Wisata Gorontalo, Akses ke Molowahu Rusak Parah
-

 Gorontalo1 month ago
Gorontalo1 month agoAnggaran Menyusut, BLT Desa Duano Ikut Terpangkas