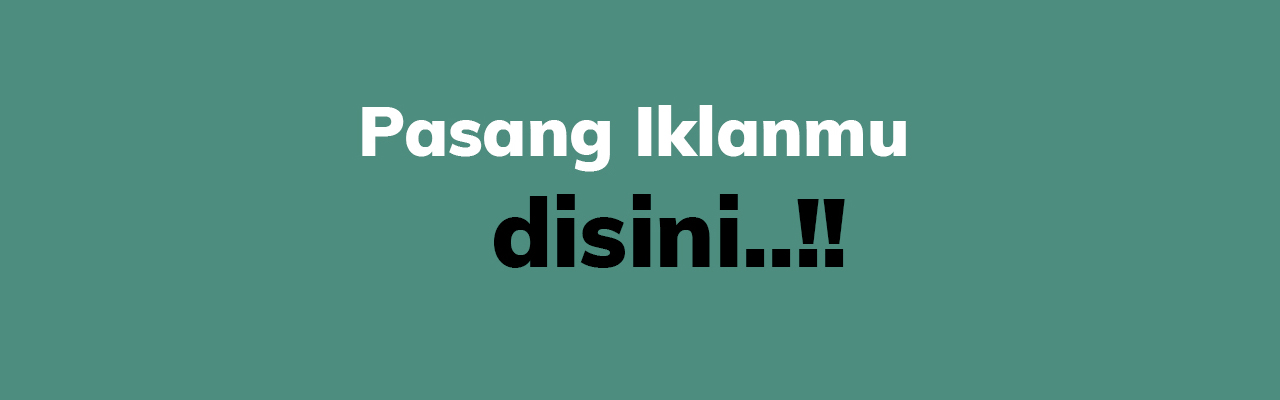Ruang Literasi
Kebijakan “Pener”, Serius? (Tanggapan atas Tulisan Makmun Rasyid)
Published
6 years agoon

Arief Abbas
Mahasiswa Pascasarjana Centre for Religious and Cross-cultural Studies, UGM. Pengurus LAKPESDAM NU Kota Gorontalo, GUSDURian Gorontalo.
Tulisan Makmun Rasyid berjudul “Kebijakan Yang Bener dan ‘Pener’” yang diterbitkan di salah satu media online Gorontalo pada hari Minggu, 8 Maret 2019 tentang pemberian Beasiswa Khusus bagi para penghapal al-Quran menarik untuk dicermati. Tulisan tersebut berangkat dari kritiknya terhadap Press Release GUSDURIan Gorontalo yang mempersoalkan pemberian Beasiswa Khusus kepada ‘penghafal al-Quran’ karena “berpotensi” diskriminatif terhadap agama lain. Bagi Makmun, pernyataan GUSDURian itu terburu-buru karena dinilainya tidak beraras pada data dan pengetahuan terhadap dunia para penghafal. Di titik ini, posisi Makmun jelas-jelas menunjukkan keberpihakannya kepada kebijakan tersebut.
Namun bagi saya, kritik Makmun ini tidak lebih dari memperlihatkan betapa abainya dia terhadap tujuan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengharuskan pemerintah agar dapat “memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya penddidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”. Apa sebenarnya “diskriminasi” yang dimaksud di sini? Sederhana. Di dalam institusi Pendidikan Tinggi—sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah—diskriminasi berarti setiap tindakan yang berpotensi untuk mengesampingkan golongan tertentu dan meninggikan golongan lainnya. Sebaliknya, Pendidikan Tinggi harusnya melaksanakan pelayanan pendidikan yang demokratis dan berkeadilan. Apa makna demokratis dan berkeadilan? Juga sederhana. Anda bisa lihat pada UU No. 12 Tahun 2012 Bab II pada poin (6) yakni “menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.”
Apakah pemberian Beasiswa Khusus terhadap para penghapal al-Quran ini “berpotensi” diskriminatif? Jawabannya bisa ya bisa tidak. Jika kebijakan ini dikeluarkan oleh Institusi Pendidikan Tinggi Islam, maka “tidak diskriminatif” karena semua mahasiswanya adalah Muslim. Berbeda jika kebijakan ini dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang, notabenenya tidak hanya direpresentasikan oleh mahasiswa Muslim, tapi juga non-Muslim, maka kebijakan ini “berpotensi” diskriminatif. Itu sebabnya, dari ratusan perguruan tinggi yang mengaplikasikan kebijakan ini, Universitas Gadjah Mada (UGM) justru menolaknya lantaran dinilai menyebabkan disparitas di antara mahasiswa yang berangkat dari latar belakang keagamaan yang berbeda-beda. Pendek kalimat, kalimat “berpotensi diskriminatif” ini dialamatkan pada sikap yang kurang “representatif” bagi lembaga pendidikan tinggi dalam mengakomodir kepentingan non-Muslim.
Lantas, apakah argumentasi ini lalu menunjukkan ketidakberpihakan saya, terlebih GUSDURian, pada para penghafal al-Quran? Tidak bisa dipahami sesempit itu juga. Bagi saya, ini terobosan cemerlang dan secara langsung mendukung kebijakan daerah Gorontalo untuk memperbanyak generasi penghapal al-Quran. Pengalaman Makmun sendiri sebagai Hafiz 30 Juz yang memberinya privilese dalam mengenyam pendidikan Strata 1 & 2 juga mengilhami saya betapa pentingnya posisi penghapal al-Quran di mata publik Indonesia saat ini, khususnya Gorontalo. Untuk dua poin ini, saya setuju dengan Makmun. Namun kemudian, ketika kita membicarakan hal ini dalam level kebijakan “potensi” diskriminasi tetap ada. Lebih dari itu, Makmun hanya melihat problem ini pada tingkatan pemangku kepentingan dan abai terhadap realitas sosiologis di lapangan. Maka, pertanyaan saya pada Makmun: pernahkah Anda bertanya—sebagaimana GUSDURian melakukannya—pada mahasiswa non-Muslim yang merasakan betapa berpotensi “diskriminatifnya” kebijakan ini? Saya kira tidak.
Selanjutnya, Makmun mengandaikan bahwa pemberian Beasiswa Khusus ini adalah kebijakan ‘pener’ dalam artian “bijaksana”, karena meskipun seseorang hafal al-Quran, mereka tetap diikat oleh prosedur dan mekanisme penerimaan MABA yang bersifat administratif. Tapi sudahkah Makmun membaca statement rektor UNG, Dr. Edwart Wolok, di salah satu media saat menghadiri penyerahan bantuan di salah satu pondok pesantren di Gorontalo bahwa “pengafal al-Quran pantas mendapatkan beasiswa tanpa test dan bebas biaya kuliah”? Bukankah statement tersebut secara tidak langsung mengafirmasi bahwa ini adalah privilese yang tidak bisa diperoleh bagi non-Muslim? Tentu saja, privilese yang saya maksud di sini memiliki cakupan yang luas.
Privilese itu, mau diraih dalam keadaan susah atau senang; terjal-berbatu atau bahkan menggunakan orang dalam sekalipun, tetaplah sebuah keistimewaan. Dengan privilese, kehidupan Anda menjadi berbeda dengan orang lain dalam artian memiliki akses yang lebih baik. Apa korelasinya dengan pemberian beasiswa bagi penghafal al-Quran? Sederhana: mereka mendapatkan “jalur khusus” untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Tetapi, hal ini secara tidak langsung juga membuktikan bahwa privilese itu nyata dalam artian menguntungkan kelas tertentu. Alhasil, jika privilese seperti ini dijadikan standar yang kita gunakan dalam mendefinisikan kebijakan, maka di mana letak “kebijaksanaan” di dalamnya?
Seharusnya, jika kebijakan ini otonom, sebagai peraturan turunan dalam potongan kalimat “memperoleh prestasi dalam bidang keagamaan” (lihat bagian (C) Persyaratan Khusus pada poin (1.a)), maka jangkauannya perlu diperluas dan tidak hanya berfokus pada satu kelas saja. Ini sebenarnya argumen kunci di dalam Press Release GUSDURian itu. Bahwa GUSDURian, sebagai proyektil ide-ide Gus Dur, dalam konteks ini hanya ingin adanya kesetaraan di dalam setiap kebijakan yang diambil oleh institusi pendidikan tinggi. Sayang, bagi Makmun, sikap GUSDURian ini justru dilihat sebagai problem insekuritas atau kecendrungan bagi seseorang yang hidup dalam ketakutan. Bahkan, Makmun menilai kalimat “berpotensi diskriminatif” ini sebagai sikap para demonian, yakni sebuah terminologi untuk menyasar kelompok orang yang merasa tidak nyaman akibat keterkejutannya berinteraksi dengan dunia luar.
Tapi sebenarnya, saya bingung; apa sebenarnya yang dimaksud Makmun dengan “dunia luar” di sini? Apakah dunia luar ini dimaksud untuk merujuk pada cara pandang seseorang dalam memandang dunia yang berbeda dari dunianya? Jika benar demikian, maka seharusnya yang telah bersikap insecure itu bukanah GUSDURian, melainkan Makmun sendiri. Sebab ia mengabaikan realitas psikologis mahasiswa non-Muslim seturut diusungnya kebijakan ini. Sebaliknya, jika kita menggunakan pertanyaan yang sama pada GUSDURian, maka jawabannya: tidak ada “dunia luar” di mata GUSDURian, sebab “aku” dan “mereka” yang selama ini diandaikan bagai oposisi biner yang saling bersebrangan itu telah cair menjadi “kita” dalam pemikiran Gus Dur, wabilkhusus pada konsep kesetaraan yang diusungnya. Bahwa “manusia memiliki martabat yang sama di mata Tuhan, maka kesetaraan ini meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi, serta marjinalisasi dalam masyarakat”. Sampai di sini, di mana letak insekuritas GUSDURian?
Lebih dari itu, apakah GUSDURian “membajak pikiran” orang lain dengan keterwakilannya sendiri? Saya kurang ngeh dengan dua kata yang Anda tandaskan itu. Anda terlalu tendensius. Bagaimana bisa GUSDURian yang berlatar belakang sebagai komunitas perwujudan ide-ide GUSDUR yang egaliter, inklusif, dan setara, bisa dikatakan sebagai perilaku “membajak”? Justru, dengan munculnya GUSDURian ke permukaan untuk mempertanyakan kebijakan ini merupakan hasil ijtihad untuk memberikan ruang bagi kelompok minor agar suara-suara mereka terwakili.
Lantas, apakah GUSDURian di sisi lain juga berusaha “menihilkan” jerih payah orang-orang yang ingin menghidupkan semangat beragama di internal Islam? Sepertinya Anda juga terlalu jauh. Inti dari release ini adalah meneropong “potensi” diskriminasi yang dihasilkan dari kebijakan pemberian Beasiswa Khusus kepada para penghapal al-Quran. Tujuannya juga tidak muluk-muluk: memberikan akses terhadap non-Muslim untuk mendapatkan privilese yang sama di mata pemangku kepentingan institusi, khususnya dalam pemberian Beasiswa Khusus dalam bidang keagamaan.
Jika demikian, apakah standar yang digunakan untuk memberikan beasiswa ini harus berporos pada mereka yang “hafal” kitab suci? Tidak juga. Asbab, Anda tidak bisa memberi standar ganda untuk melegitimasi sebuah kebijakan pada mahasiswa yang heterogen dalam konteks agama yang mereka yakini. Toh saya juga percaya Anda mahfum bahwa sedikit sekali—untuk tidak menyebut ‘tidak ada’—mahasiswa non-Muslim yang bisa menghafal kitab sucinya. Untuk itu, seandainya release GUSDURian ini dapat menjadi bahan pertimbangan, pihak kampus dapat memberikan ketentuan-ketentuan lain bagi mahasiswa non-Muslim agar mendapat Beasiswa Khusus dalam bidang keagamaan tersebut dan tidak termasuk dalam daftar katagori “Beasiswa Penghafal al-Quran”.
Terakhir, bagi saya, privilese itu sekali lagi nyata dan membentuk rantai kesenjangan. Tapi saya kira pemangku kepentingan kita bisa mencoba memangkasnya dengan memberikan kesempatan pada warga negara yang tidak memilikinya agar bisa memperoleh akses setara dengan yang memilikinya dan, tentu saja, tidak harus dengan standar yang sama. Jika ada yang perlu diminta untuk bersikap adil, maka itu adalah pemangku kepentingan. Dalam konteks ini, bisa dengan langkah sederhana, misalnya: dengarkan mereka mahasiswa non-Muslim yang ada di UNG. Apakah kebijakan ini diskriminatif atau tidak. Bukan mengarahkan istilah “diskriminatif” pada kelompok sendiri. Itu tidak fair.***
Ruang Literasi
Ketika Realitas Dipalsukan: Deepfake dan Masa Depan Demokrasi Digital
Published
4 weeks agoon
28/01/2026
Oleh: Mohammad Adrian Latief
Di era digital, kebenaran tak lagi berdiri di atas fondasi yang kokoh. Teknologi yang awalnya diciptakan untuk memudahkan kehidupan manusia kini juga menelurkan sisi gelap yang mengancam tatanan sosial dan politik. Salah satu wajah paling menakutkan dari perkembangan itu adalah deepfake — teknologi berbasis kecerdasan buatan yang mampu memalsukan wajah, suara, serta gerak seseorang secara nyaris sempurna.
Ketika realitas dapat direkayasa sedemikian rupa hingga tampak meyakinkan, masa depan demokrasi digital justru berada di ujung tanduk.
Kebenaran yang Tergadaikan
Demokrasi dibangun di atas satu prinsip utama: hak warga negara atas informasi yang benar. Namun, kehadiran deepfake mengaburkan batas antara fakta dan fiksi. Sebuah video yang menampilkan sosok pejabat publik mengucapkan pernyataan provokatif—padahal tidak pernah terjadi—dapat viral dalam hitungan menit. Dalam atmosfer politik yang sudah terpolarisasi, rekayasa semacam ini bukan sekadar bentuk disinformasi, tetapi senjata digital yang mampu menjatuhkan reputasi, memicu konflik, bahkan menggoyang legitimasi hasil pemilu.
Bahaya terbesar deepfake bukan hanya terletak pada kemampuannya menipu mata dan telinga manusia, tetapi juga pada dampak jangka panjang terhadap kepercayaan publik. Ketika masyarakat sadar bahwa video dan rekaman suara bisa dimanipulasi, muncul fenomena liar’s dividend, yakni kondisi ketika pelaku kejahatan atau politisi bermasalah dengan mudah menepis bukti autentik dengan alasan “itu hanya deepfake.” Akibatnya, kebenaran kehilangan daya ikatnya, dan ruang publik tenggelam dalam skeptisisme total.
Demokrasi yang Digital, Ancaman yang Nyata
Dalam konteks demokrasi digital, di mana percakapan politik, kampanye, dan partisipasi publik berlangsung secara daring, ancaman ini menjadi semakin nyata. Algoritma media sosial yang memprioritaskan konten sensasional ikut mempercepat penyebaran video manipulatif tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, masyarakat bukan hanya konsumen informasi, melainkan target manipulasi psikologis yang dirancang secara sistematis.
Namun, menyalahkan teknologi semata adalah pandangan yang keliru. Deepfake hanyalah alat; yang menentukan dampaknya adalah bagaimana manusia, lembaga, dan negara meresponsnya.
Jalan Panjang Menyelamatkan Demokrasi
Masa depan demokrasi digital sangat bergantung pada tiga hal: regulasi yang adaptif, literasi digital yang kuat, dan tanggung jawab etis platform teknologi.
Negara harus hadir dengan kebijakan hukum yang tidak gagap terhadap perkembangan digital. Regulasi perlu tegas menindak penyalahgunaan konten manipulatif tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.
Di sisi lain, masyarakat perlu dibekali kemampuan verifikasi kritis – kebiasaan untuk meragukan, memeriksa, dan tidak langsung mempercayai apa yang tampil di layar. Tanpa kesadaran itu, publik menjadi tanah subur bagi propaganda digital.
Sementara itu, perusahaan teknologi tidak bisa lagi bersembunyi di balik dalih “netralitas platform.” Mereka memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendeteksi serta meminimalisasi penyebaran deepfake, termasuk dengan memperkuat sistem identifikasi konten berbasis autentikasi digital.
Menjaga Realitas, Menyelamatkan Demokrasi
Pada akhirnya, pertarungan melawan deepfake bukan hanya tentang teknologi melawan teknologi, tetapi tentang nilai dan integritas di era informasi. Demokrasi hanya bisa bertahan jika kebenaran tetap dijunjung tinggi sebagai kepentingan bersama.
Ketika realitas bisa dipalsukan, kejujuran, kewaspadaan, dan tanggung jawab kolektif menjadi tameng terakhir kita. Tanpa itu, demokrasi berisiko berubah menjadi ilusi — tampak nyata di layar, namun hampa di dalamnya.[/responsivevoice]

Penulis: Ulan Bidi | Dosen FKIP Universitas Pohuwato
Gorontalo – Seorang pemimpin sejatinya adalah sosok yang mampu mengayomi dan menciptakan rasa nyaman bagi rakyat yang dipimpinnya. Kalimat ini terlintas begitu kuat dalam benakku ketika terjaga dari sebuah mimpi semalam.
Dalam mimpi itu, aku memarahi seorang mahasiswa karena kesalahan kecil, sementara kepada mahasiswa lain yang juga berbuat salah, aku justru bersikap lembut. Menariknya, mahasiswa yang kuperlakukan dengan baik adalah sosok yang secara pribadi aku sukai, sedangkan yang dimarahi adalah mahasiswa yang kerap membuatku sedikit jengkel. Padahal, dari sekian banyak mahasiswa yang kutemui, hanya dia yang sesekali membuatku kesal. Aku jadi bertanya-tanya, mengapa aku bermimpi seperti itu?
Refleksi dari mimpi tersebut membuatku teringat pada penelitian Ahmad Fauzi (2023) berjudul “Dinamika Relasi Dosen–Mahasiswa: Studi Kasus Ketidaksopanan di Perguruan Tinggi Negeri.” Hasil penelitian itu menyoroti aspek psikologis hubungan antara dosen dan mahasiswa, terutama terkait perilaku yang mengganggu proses belajar-mengajar.
Fauzi menemukan bahwa sikap mahasiswa yang meremehkan penjelasan dosen atau membuat kelompok diskusi sendiri saat perkuliahan menjadi sumber ketidaknyamanan terbesar. Ia menyimpulkan bahwa, meski sebagian besar mahasiswa tetap menjaga sopan santun, masih ada segelintir yang bersikap konfrontatif — misalnya, mendebat nilai dengan nada tinggi — sehingga memengaruhi kenyamanan dan kinerja dosen di kampus.
Dalam praktik kehidupan akademik, sepatutnya mahasiswa menaruh hormat kepada dosen sebagai guru, bukan sebaliknya dosen yang harus selalu memahami tingkah laku mahasiswanya. Sebab, restu guru adalah berkah yang harus diraih dalam menuntut ilmu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ath-Thabrani dari Abu Hurairah:
“Belajarlah kalian ilmu, dan belajarlah untuk ilmu tersebut ketenangan dan kewibawaan, serta rendahkanlah diri kalian kepada orang yang kalian pelajari ilmunya (guru).”
Namun, aku tidak ingin berhenti di sini. Mimpi tadi menyadarkanku bahwa dalam posisi apa pun, termasuk sebagai dosen, diperlukan kebijaksanaan dalam memimpin. Pemimpin, baik di ruang kuliah maupun di tengah masyarakat, tidak boleh bersikap pilih kasih. Ia harus mampu membimbing dengan kesabaran dan kelembutan, tanpa membeda-bedakan siapa pun.
Demikian pula seorang pemimpin di tengah masyarakat. Ia tidak boleh memihak satu kelompok dan mengabaikan kelompok yang lain, apalagi hanya membela pihaknya sendiri. Sikap tersebut jelas bertentangan dengan nilai keadilan. Sebagaimana pepatah mengatakan, “Menimbang sama berat, mengukur sama panjang,” yang berarti pemimpin dituntut berlaku objektif.
Jika dalam satu timbangan terdapat keluarga dan di sisi lain orang asing, maka keputusan harus berlandaskan kebenaran, bukan kedekatan. Bila seorang pemimpin lalai menegakkan keadilan, rakyatlah yang akhirnya menanggung akibatnya.
Hubungan antara dosen dan mahasiswa memang berbeda dengan antara pemimpin dan rakyat. Guru harus dihormati, sedangkan pemimpin harus melayani. Bukan sebaliknya, pemimpin yang meminta dilayani. Karena itu, adab harus selalu didahulukan daripada ilmu. Sebab, jika hanya berilmu tanpa beradab, manusia bisa terjerumus dalam kesombongan — sebagaimana Iblis yang ilmunya tinggi, namun diusir dari rahmat Allah karena keangkuhannya.
Pada akhirnya, segala ilmu dan jabatan hanyalah titipan. Ilmu manusia hanyalah setetes dari samudra ilmu Allah Subhanahu wa Ta’ala. Maka, tidak ada alasan untuk bersikap sombong. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an:
“Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong” (QS. Al-Isra: 37).

Tojo Una-Una – Aktivitas pertambangan pasir milik PT Indo Tambang Pasir Utama di Desa Balanggala, Kabupaten Tojo Una-Una (Touna), Sulawesi Tengah, menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati lingkungan. Sejumlah pihak menilai kegiatan tambang tersebut berpotensi merusak ekosistem mangrove yang menjadi benteng alami kawasan pesisir.
Pemerhati lingkungan asal Touna, Hersal Febrian, secara terbuka mempertanyakan dampak serius aktivitas pertambangan terhadap kelestarian mangrove. Ia menyebut bahwa beberapa kawasan mangrove di sekitar pesisir yang masih masuk dalam wilayah konsesi perusahaan diduga ikut diratakan akibat kegiatan pertambangan.
Berdasarkan dokumen resmi, PT Indo Tambang Pasir Utama mengantongi Izin Usaha Produksi (IUP) bernomor 27072200825840001 dengan luas lahan konsesi mencapai 24 hektar. Namun, hasil temuan lapangan yang diungkapkan sejumlah warga menunjukkan adanya aktivitas yang berpotensi mengancam kelestarian vegetasi mangrove di sekitar lokasi tersebut.
“Apakah Dinas Lingkungan Hidup mengetahui bahwa saat ini pemerintah sedang gencar melaksanakan Gerakan Nasional Perlindungan Ekosistem Mangrove sebagai implementasi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2025? Lalu bagaimana bentuk pengawasan terhadap aktivitas tambang ini?” ujar Hersal, Senin (20/01/2026).
Ia menegaskan bahwa mangrove bukan sekadar vegetasi pantai, melainkan ekosistem penting yang berfungsi sebagai pelindung alami dari abrasi, penahan badai, hingga penyerap karbon untuk mengurangi dampak perubahan iklim.
“Apakah perusahaan sadar bahwa mangrove adalah benteng utama menghadapi perubahan iklim dan abrasi? Jika area ini rusak, siapa yang bertanggung jawab atas dampak ekologisnya?” tegas Hersal.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti lemahnya transparansi perusahaan dan instansi terkait dalam menjawab kekhawatiran publik. Menurutnya, praktik eksploitasi di kawasan pesisir tanpa mitigasi jelas berpotensi memperburuk krisis ekologi yang kini menjadi perhatian global.
Sorotan publik terhadap kasus ini muncul beriringan dengan komitmen kuat pemerintah pusat dalam memperkuat perlindungan hutan mangrove. Belum lama ini, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) menggelar kegiatan penanaman mangrove yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia sebagai simbol penguatan gerakan nasional perlindungan ekosistem pesisir.
Menurut Hersal, kondisi di Desa Balanggala justru kontradiktif dengan semangat program nasional tersebut. Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap perizinan dan kegiatan PT Indo Tambang Pasir Utama serta meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Tojo Una-Una bersikap terbuka terkait langkah pengawasan dan penegakan aturan lingkungan.
“Jangan sampai komitmen nasional perlindungan mangrove hanya menjadi slogan, sementara di lapangan, habitat penting pesisir dirusak tanpa pengawasan yang jelas,” pungkas Hersal.

Rumah Dekan Jadi Saksi! LD Al Fatih FIS UNG Hidupkan Ramadan dengan Tadarusan

Kebersamaan di Bulan Suci: Pemkab Pohuwato Gelar Buka Puasa di Wanggarasi

Warganet Kaget! Ini Isi Menu Bergizi Gratis Senilai Rp15 Ribu

Namanya Dicatut Media, Wakil Dewan Pengawas KUD Dharma Tani Angkat Bicara

Tujuan Mulia Tersandung Kritik, MBG Gorontalo Ramai Dikeluhkan di Medsos

Tertib Administrasi! Pemkab Pohuwato Atur Jam Kerja ASN Selama Ramadan

Tak Sekadar Rayakan HUT, Gerindra Gorontalo Ulurkan Kasih untuk Anak Yatim dan Piatu

Pemuda Bergerak: Karang Taruna Patriot Bilungala Kukuhkan Silaturahmi

Sudah Lengkap Berkasnya, Ahli Waris Pohuwato Masih Menanti Klaim Jaminan Kematian

Suara Tradisi di Tengah Zaman: Koko’o Bilungala Tetap Berdentum Tanpa Sound System

PKK GELAR JAMBORE PKK TINGKAT KABUPATEN GORUT

Kota Gorontalo Peringkat kedua Internet Paling Ngebutt se-Indonesia

PIMPIN RAPAT PENYERAPAN PROGRAM, BUPATI PUAS HASIL EVALUASI

PEMKAB GORUT BERIKAN BANTUAN RP. 1 JUTA/ORANG UNTUK JAMAAH CALON HAJI

Dua Kepala Desa Di copot Bupati
Terpopuler
-

 Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months agoJIKA 100 TAHUN LAGI ORANG MENCARI GORONTALO 2025
-

 Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months agoBerawal dari Arahan Wali Kota, Kelurahan Biawao Raih Juara Pemungutan PBB-P2
-

 Gorontalo3 months ago
Gorontalo3 months agoAbai dan Bungkam: Refleksi Elit Gorut Atas Tragedi Julia
-

 Advertorial2 months ago
Advertorial2 months agoBukan Sekadar Imbauan! Wali Kota Gorontalo Tegas Larang Petasan di Malam Tahun Baru
-

 Gorontalo2 months ago
Gorontalo2 months agoPotret Ironi Wisata Gorontalo, Akses ke Molowahu Rusak Parah
-

 Gorontalo1 month ago
Gorontalo1 month agoAnggaran Menyusut, BLT Desa Duano Ikut Terpangkas
-

 News3 months ago
News3 months agoRibuan Netizen Buru Link Video Sensitif Inara
-

 Gorontalo1 month ago
Gorontalo1 month agoJanji Potong Jari Berbuah Nyata? Ka Kuhu Ditetapkan Tersangka